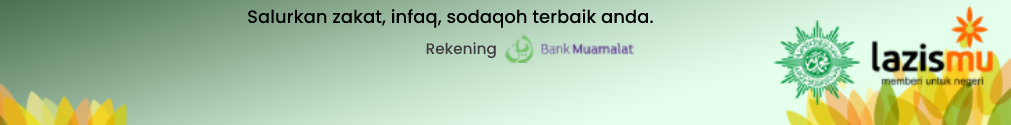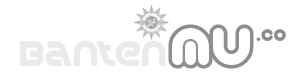Oleh: Anggara Wahyu Adhari, S.ST., M.S.E. (Anggota PCM Pandeglang)

Sudah sejak lama kita mengetahui bahwa nilai mata uang dari masing-masing negara berbeda jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah. Namun, pernahkah kita merasa penasaran mengapa ini terjadi? Apakah nilai ini telah ditentukan oleh sesuatu atau terjadi secara alamiah? Mengapa kita tidak menggunakan mata uang yang sama di seluruh dunia? Mari kita telisik lebih dalam alasan di balik perbedaan nilai mata uang setiap negara.
Pada awal terciptanya mata uang, kedudukannya adalah sebagai “perwakilan” dari logam mulia (emas) yang disimpan oleh suatu negara. Inilah yang kita kenal dengan standar emas. Dengan standar emas, pemerintah atau bank sentral mengatur nilai mata uang dengan cadangan emas yang mereka miliki. Artinya, jumlah uang yang dapat dikeluarkan oleh negara dibatasi oleh jumlah emas yang dimiliki.
Kelebihan dari sistem ini adalah memberikan stabilitas karena nilai mata uang terkait langsung dengan nilai emas, yang cenderung stabil dalam jangka panjang. Hal ini membantu mengendalikan inflasi karena pemerintah tidak bisa mencetak uang secara sembarangan tanpa cadangan emas yang memadai. Namun, pada akhirnya, banyak negara meninggalkan sistem standar emas, terutama selama abad ke-20, karena keterbatasan dalam menyesuaikan jumlah uang beredar dengan kebutuhan ekonomi yang terus berkembang.
Inggris selama tahun 1821 hingga 1914 menerapkan standar emas. Mata uang Inggris (Pound sterling) mewakili sejumlah nilai emas. Inggris mempertahankan standar emas ini hingga Perang Dunia I (1914). Dikarenakan kebutuhan dana besar-besaran, Inggris mulai mencetak lebih banyak uang dan meninggalkan standar emas.
Amerika Serikat mengadopsi standar emas pada tahun 1879, dan Dolar AS dapat ditukar dengan emas dengan nilai tetap. Namun selama Depresi Besar (Great Depression) pada tahun 1933, Presiden Franklin D. Roosevelt mengakhiri standar emas untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah AS akhirnya menetapkan bahwa dolar tidak lagi harus didukung atau “mewakili” nilai emas dalam perekonomian AS. Puncaknya pada tahun 1971, Presiden Amerika Richard Nixon mengakhiri konvertibilitas dolar ke emas secara internasional. Peristiwa ini dikenal luas dengan sebutan Nixon Shock (Kejutan Nixon). Negara-negara asing yang memegang cadangan dolar tidak lagi bisa menukar dolar mereka dengan emas dari Amerika Serikat. Kebijakan ini mengakhiri standar emas sepenuhnya dan dunia beralih ke sistem uang fiat.
Uang fiat adalah uang yang didasarkan pada kepercayaan publik kepada pemerintah yang mengeluarkan uang tersebut. Uang fiat tidak lagi mewakili nilai komoditas apapun sebagaimana standar emas. Uang fiat murni berdiri di atas kepercayaan masyarakat. Anda boleh menyebutnya “uang palsu” jika Anda tidak percaya dengan pemerintah yang mengeluarkannya. Anda juga boleh menyebutnya “uang ajaib” karena selembar kertas yang nilainya hanya berasal dari kepercayaan namun bisa dibelanjakan untuk mendapatkan barang dan jasa.
Dikarenakan uang fiat ini tidak berdasarkan apapun selain kepercayaan, maka nilainya tidak terikat oleh apapun kecuali hanya pada jumlahnya yang beredar. Oleh karena itu, berlakulah hukum penawaran dan permintaan (supply and demand) sebagaimana komoditas lainnya. Jika jumlahnya banyak beredar maka tingkat kelangkaannya berkurang sehingga nilainya pun berkurang. Begitu sebaliknya jika jumlah uang yang beredar turun, maka menjadi semakin langka sehingga nilainya meningkat.
Sebagai contoh, kita pernah membeli 1 mangkok mie ayam di tahun 1994 seharga Rp1.000 dan sekarang di tahun 2024 harga 1 mangkok mie ayam Rp20.000. Ini menandakan nilai rupiah telah mengalami penurunan 20 kali sejak tahun 1994. Uang Rp20.000 jika dibelikan mie ayam di tahun 1994 akan dapat 20 mangkok. Fenomena ini disebut inflasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena jumlah uang yang beredar saat ini 2024 sudah sebanyak 20 kali lipat dibandingkan di tahun 1994.
Jika Anda penasaran mengapa uang beredar semakin banyak, Anda dapat membaca selengkapnya di dalam artikel saya yang berjudul “Bagaimana Uang Tercipta di Dunia Modern?”
Jumlah permintaan akan uang fiat di dalam negeri biasanya dalam bentuk utang di bank. Suku bunga pinjaman yang rendah akan menarik orang berbondong-bondong meminjam uang di bank. Akibatnya jumlah permintaan terhadap uang fiat tersebut meningkat drastis. Artinya, jumlah fiat yang beredar semakin banyak yang mengakibatkan nilainya turun. Inilah apa yang kita kenal dengan istilah inflasi yaitu kondisi nilai uang yang turun sehingga kita butuh lebih banyak uang untuk membayar barang yang sama. Masih ingat contoh mie ayam di atas? Begitulah kira-kira gambarannya.
Selain tingkat suku bunga pinjaman, jumlah uang fiat juga dipengaruhi oleh perdagangan internasional. Misalkan Indonesia ingin membeli (impor) komputer dari Amerika Serikat dalam jumlah besar, maka Amerika Serikat sebagai penjualnya hanya mau dibayar menggunakan dolar AS. Mereka tidak mau komputer mereka dibayar menggunakan Rupiah Indonesia. Oleh sebab itulah, Indonesia harus “membeli” (baca: menukarkan) dolar AS dengan Rupiah untuk dapat melakukan transaksi.
Hal ini menjadikan permintaan terhadap dolar AS meningkat. Tentu saja yang membeli komputer dari AS tidak hanya Indonesia saja, masih banyak negara lain juga yang ingin membeli komputer AS. Sehingga semakin banyak permintaan terhadap dolar AS, maka nilai dolar AS semakin tinggi karena banyak diminati. Tetapi bagai pisau bermata dua, jika nilai dolar AS semakin tinggi maka negara-negara yang ingin membeli barang-barang dari AS harus membayar semakin mahal. Jika sudah terlampau mahal maka mereka akan memilih opsi lain, apakah akan membeli barang dari negara lain atau memproduksinya sendiri di dalam negaranya masing-masing.
Mungkin kemudian muncul pertanyaan: mengapa tidak semua negara menggunakan mata uang yang sama, seperti dolar dunia, agar kita tidak memerlukan nilai tukar dan segala kerepotan ini? Ide ini mungkin terdengar bagus, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Kita bisa melihat contoh Euro, mata uang tunggal yang digunakan oleh negara-negara dalam Uni Eropa. Mata uang bersama ini memang memudahkan masyarakat Eropa untuk bepergian lintas negara tanpa perlu menukarkan uang. Namun, tantangannya adalah setiap negara anggota harus menyerahkan kendali atas kebijakan moneter mereka ke Bank Sentral Eropa. Artinya, jika sebuah negara mengalami masalah ekonomi, mereka tidak bisa langsung mengubah kebijakan moneternya sendiri tanpa memikirkan dampaknya bagi negara lain.
Krisis keuangan yang dialami Yunani pada 2009, misalnya, berdampak besar bagi negara-negara lain di Uni Eropa. Pada saat itu, Yunani menghadapi masalah utang yang sangat besar sehingga mengancam stabilitas ekonominya. Karena Yunani menggunakan Euro, yang juga digunakan oleh negara-negara Uni Eropa lainnya dalam Zona Euro, krisis ini berdampak langsung pada negara-negara tersebut. Jadi, saat ekonomi Yunani goyah, nilai Euro ikut terpengaruh. Negara-negara dengan ekonomi kuat seperti Jerman ikut terdampak karena mereka menggunakan mata uang yang sama.
Jika Yunani masih menggunakan mata uangnya sendiri, maka dampak krisis ini mungkin hanya terbatas pada negara itu saja. Namun, karena menggunakan Euro, dampak krisis ini menyebar ke negara-negara lain di Eropa yang juga menggunakan Euro, termasuk negara-negara dengan ekonomi yang lebih stabil. Ini menunjukkan risiko dari penggunaan mata uang tunggal di seluruh dunia. Jika semua negara di dunia menggunakan mata uang yang sama, maka masalah ekonomi satu negara dapat memicu krisis global.
Bayangkan jika seluruh dunia menggunakan satu mata uang yang sama, dan kemudian satu negara besar mengalami krisis keuangan. Krisis tersebut bisa menyebabkan penurunan nilai mata uang global, sehingga ekonomi negara-negara lain juga akan terdampak, walaupun sebenarnya mereka tidak mengalami masalah ekonomi yang sama. Risiko ini menunjukkan kelemahan dari penggunaan mata uang tunggal di tingkat global.
Selain itu, tidak semua negara ingin membuat mata uang mereka sekuat mungkin. Setiap negara memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda. Negara yang banyak mengimpor, seperti Singapura, mungkin menginginkan mata uang yang kuat agar impor menjadi lebih murah. Sebaliknya, negara yang banyak mengekspor, seperti Tiongkok, mungkin menginginkan mata uang yang lebih lemah agar produk-produknya lebih murah bagi negara lain. Ini sebabnya Tiongkok sering dituduh sengaja menurunkan nilai mata uangnya, yang dikenal sebagai devaluasi mata uang. Dengan menurunkan nilai mata uang, produk-produk ekspor Tiongkok menjadi lebih terjangkau di pasar internasional.
Banyak faktor memengaruhi kebijakan moneter suatu negara, dan setiap kebijakan memiliki kelebihan dan risiko masing-masing. Maka dari itu, stabilitas dan kekuatan mata uang bukanlah hal yang seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi negara tersebut. Sehingga terjawab sudah pertanyaan diawal tulisan ini bahwa tidak memungkinkan bagi seluruh negara menggunakan mata uang yang sama.